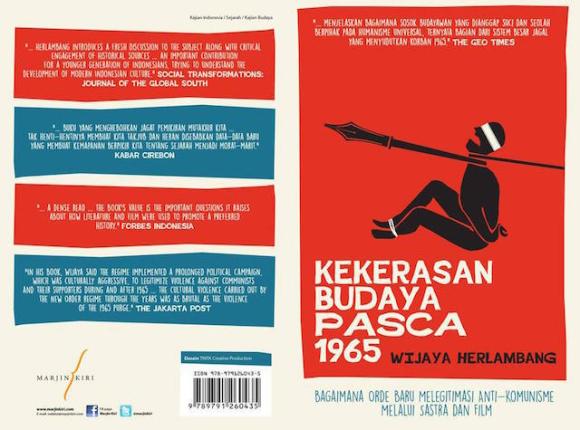Wartawan, ia ada dan selalu ada untuk menyampaikan berita. Dari berita baik hingga kabar buruk, dari berita lokal hingga internasional, dari yang sifatnya remeh temeh sampai yang menggemparkan macam gejolak politik dan tindak korupsi.
Pekerjaan wartawan memang menghimpun informasi dan menyampaikan berita, namun kadang tidak kita sadari, bahwa wartawan juga berperan sebagai saksi sejarah. Untuk membuktikannya, tak perlu melihat jauh pada sepak terjang wartawan hebat di Perang Vietnam atau Perang Teluk, cukup melihat kembali Kota Bandung di 60 tahun yang silam. Kala itu, Kota Bandung menjadi magnet bagi para wartawan dari berbagai penjuru dunia. Tahun 1955 Kota Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 April. Tentu saja, ketika itu banyak wartawan handal nimbrung di Bandung.
Salah satu wartawan legendaris Indonesia, Rosihan Anwar (alm) menuliskan pengalamannya meliput KAA pada 1955 dalam bukunya Petite Histoire Indonesia (2004). Dalam tulisannya itu, ia mengungkapkan: “Di Bandungnya Indonesia, di situlah bertemu untuk pertama kalinya begitu banyak pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika, membicarakan perihal perjuangan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Di situlah bertemu tokoh-tokoh penting seperti Sukarno, Nehru, Ali Khan, Zhou En-lai, U Nu, Kotelawala, Nasser dll.” Wartawan tiga zaman itu pun bercerita bukan sekedar bagaimana KAA berlangsung, namun juga menuturkan pengalaman pribadinya selama peliputan. Dan ini menjadi menarik, karena tulisan itu pulalah kita bisa tahu peran wartawan sebagai saksi sejarah, juga bagaimana wartawan melakukan pekerjaannya di tengah sebuah peristiwa besar macam KAA.
Pada peristiwa KAA itu, wartawan-wartawan terkemuka di Indonesia datang dan meliput. Rosihan Anwar saat itu menjadi Editor harian Pedoman yang cukup banyak pembacanya. Ada pula Mochtar Lubis dari harian Indonesia Raya, B.M. Diah dari harian Merdeka, Suardi Tasrif dari Abadi, Adam Malik dari Antara, Djamaluddin Adinegoro dari PIA, Mohamad Isnaini dari Suluh Indonesia, Mahbub Djunaidi dari Duta Masyarakat. Ada pula Umar Said dari Harian Rakyat. Orang-orang media massa terdiri dari wartawan surat kabar, wartawan radio, wartawan foto, kolumnis dalam negeri dan luar negeri, seluruhnya berjumlah 500 orang. Meski demikian, yang tercatat hanya berjumlah 377 wartawan, terdiri dari 214 wartawan luar negeri dan 163 wartawan dari Indonesia.
Ketika itu, wartawan-wartawan Indonesia datang dengan perlengkapan yang seadanya, kamera pun belum banyak dipakai. Tidak ada barisan kamera yang bersifat dominan karena televisi belum lazim sebagai peliput. Yang ada hanya kamera untuk membuat film dokumenter atau jurnal berita.
Markas Para Wartawan di Swarha
Menurut keterangan Rosihan Anwar dari bukunya Petite Histoire Indonesia, para wartawan menginap di sebuah hotel bertingkat yang terletak di depan kantor pos. Hotel tersebut bernama Swarha. Kala itu, para wartawan memang menginap di Hotel Swarha karena Hotel Savoy Homman dan Hotel Preanger seluruh kamarnya sudah penuh dipakai para delegasi peserta KAA. Panitia KAA saat itu memang secara khusus menyediakan Hotel Swarha sebagai tempat menginapnya para wartawan. Pertimbangannya, Hotel Swarha yang terletak di di Jalan Raya Timur (sekarang Jalan Asia Afrika/samping Mesjid Agung) itu berada di seberang kantor pos besar, sehingga memudahkan para wartawan mengirimkan berita lewat telegram.
Lokasi Hotel Swarha cukup menguntungkan bagi para wartawan, karena terletak tidak jauh dari dari Gedung Merdeka. Jadi, tidak diperlukan ongkos khusus untuk mencapai lokasi konferensi, cukup dengan berjalan kaki. Rosihan dalam catatannya menyebutkan bahwa Hotel Swarha sebagai hotel yang serba sederhana. Hotel ini berlantai empat; lantai pertama tidak memiliki kamar, sementara di lantai kedua hingga keempat, masing-masing memiliki delapan kamar.

Hotel Swarha sebetulnya merupakan sebuah gedung peninggalan Belanda yang dibangun pada 1930-1950 hasil rancangan Wolf Schoemaker dengan gaya arsitektur eklektik beratap tumpuk seperti gaya Cina. Pada tahun 1950-an gedung ini sengaja diperluas untuk kepentingan KAA. Nama Swarha sendiri diambil dari nama sang pemilik gedung itu.
Hotel Swarha benar-benar menjadi markas besar bagi para wartawan peliput KAA, baik dalam dan luar negeri. Selain Rosihan Anwar yang menginap di hotel tersebut, ada pula Mochtar Lubis wartawan yang pernah dipenjara oleh Pemerintah Orde Lama. Mochtar pernah bekerja di Kantor Berita Antara, lalu mendirikan surat kabar Indonesia Raya tahun 1949. Ia juga terkenal sebagai koresponden perang ketika pecah pertempuran Korea Utara dan Korea Selatan pada 1950. Di Hotel ini pula sastrawan penulis novel Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisjahbana menginap, bersama Sudjatmoko, dan juga Syahrir.
Selain tokoh-tokoh pers nasional, beberapa tokoh pers terkemuka di dunia pun turut menginap di Hotel Swarha. Ada Arthur Conte, seorang wartwan terkemuka asal Prancis. Conte begitu dikenal karena sempat menjabat sebagai Presiden Majelis Uni-Eropa tentang Peradaban Barat. Tak kalah dengan Rosihan Anwar, Conte pun menuliskan pengalamannya selama meliput KAA dalam sebuah buku yang berjudul Bandoeng, Tournat de l’Histoire (Bandung, Titik Balik dalam Sejarah). Conte mengisahkan, para wartawan tinggal di sebuah markas yang sangat sempit. Markas yang dimaksud itu tidak lain adalah Hotel Swarha.
Ada pula wartawan berdarah Afrika-Amerika yang turut bermarkas di Hotel Swarha, ia adalah Richard Wright. Selain sebagai wartawan, Wright justru dikenal sebagai penulis kawakan asal Amerika yang beberapa kali dicalonkan sebagai pemenang Nobel Sastra. Ia merupakan salah satu penulis yang concern dengan masalah rasialisme. Lewat novelnya yang berjudul Uncle Tom’s Cabin dan Native Son, Wright mencoba menggambarkan realitas sosial dan diskriminasi yang terjadi di Amerika. Isu-isu ini tentu saja sejalan dengan visi KAA yang mencoba menegakkan nilai-nilai kemerdekaan secara universal. Seperti pula Rosihan Anwar dan Arthur Conte, Richard Wright pun menuliskan pengalamannya selama meliput KAA dalam bukunya yang berjudul The Color Curtain, A Report on The Bandung Conference yang terbit pada 1956. Buku-buku yang ditulis oleh para wartawan itu, menggambarkan betapa mereka, para wartawan, bukan sekedar menjalankan tugas, namun mereka pun memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendokumentasian sejarah; sejarah yang boleh jadi turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan negara-negara di dunia.
Kisah seputar Peliputan

Dalam hal peliputan KAA, para wartawan ini punya kisah tersendiri. Misalnya tentang dinamika peliputan di Gedung Merdeka, seperti yang dikemukakan oleh Rosihan Anwar. Awak media yang jumlanya banyak, ternyata bisa ditampung di dalam ruangan gedung karena mereka tidak menumpuk pada saat yang sama, namun memencar mencari berita, pergi ke bungalo-bungalo di Cimbuleuit, Cipaganti, dan Lembang, di mana para delegasi menginap. Di dalam Gedung Merdeka, untuk menciptakan hubungan lancar antara sekretariat dan pers seperti penyiapan dan penyebaran press release, pemerintah sengaja memanggil pulang tenaga-tenaga diplomat di kedutaan besar RI untuk ditugaskan dalam pekerjaan Public Relations.
Kerja keras wartawan dalam meliput dikemukakan pula dalam Harian Merdeka (20 April 1955) disebutkan bahwa Wartawan bekerja berdesak-desakan padahal sudah kelelahan. Dapat kita bayangkan, pada saat itu sekian ratus wartawan bekerja pada beragam media yang berbeda, dari negara dan suku bangsa yang berdeba-beda pula, dan dengan beragam kesibukan. Mulai dari hilir-mudik meliput di Gedung Merdeka hingga ke penginapan-penginapan para delegasi, menghimpun informasi dan mengolahnya di Gedung Swarha. Tak sampai di situ, informasi yang didapat tentu harus dikirim pada kantor berita masing-masing, maka kantor pos pun ketika itu boleh jadi selalu dipadati oleh sekian banyak wartawan yang akan mengirimkan telegram. Untuk kepentingan peliputan, saat itu kantor pos Bandung sengaja menambah kapasitas pengiriman telegram dari 100 kata menjadi 200 kata.
Tentu kondisi saat itu sangat jauh berbeda dengan kondisi masa kini ketika semuanya dipermudah dengan internet. Dahulu sistem kerja peliputan serba manual. Wartawan lazim memiliki kemampuan stenografi karena alat rekam tentulah belum begitu populer ketika itu, mesin tik pun menjadi teman akrab, dan kamera manual menjadi barang yang cukup mewah, ditambah lagi dengan proses pengiriman berita yang harus melalui telegram atau pos. Ada keterangan menarik yang dikemukakan oleh Paul Tedjasurja, salah satu fotografer KAA yang masih hidup hingga saat ini. Ketika KAA berlangsung, Paul masih berusia 25 tahun. Menurutnya, saat itu Harian atau Koran yang mengutus para wartawan belum memiliki fotografer sendiri, sehingga para wartawan memperoleh photo dari para press agency. Press agency inilah yang dilakoni Paul, dan ia menjual hasil jepretannya yang diperoleh dari pagi hingga malam pada Koran-koran lokal. Tentu saja kamera yang digunakannya pun masih sederhana, yaitu kamera selica tipe lama.
Terbayang sudah, kerja wartawan di masa itu sangatlah berat. Pantaslah kita semua angkat topi untuk kerja para wartawan di masa itu. (H.G. Budiman, dari berbagai sumber)